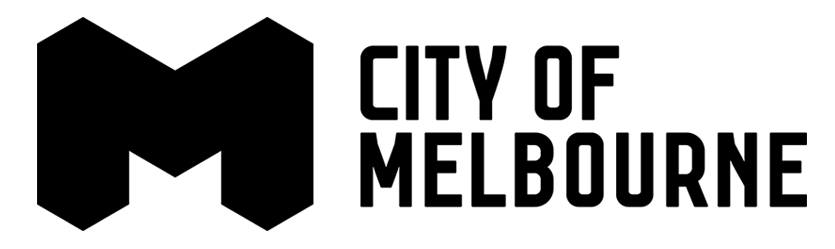Read this introduction in English
Puisi-puisi dalam kumpulan ini merunut siklus-siklus perjalanan manusia yang bertumpang-tindih sejak kelahiran sampai kematian, melintasi ruang dan waktu yang kita hitung dengan derap kaki dan ukuran puitika. Berkelana di dalam lingkup keluarga dan masyarakat, perjalanan kita akan memerankan warisan spesies ini, persaudaraan dan kekerasan—dua sisi dari perjuangan yang sama yang sangat menginginkan kedekatan yang bisa meniadakan pemisah jarak, waktu dan psikologi antara sosok ‘liyan’ dan diri sendiri. Melalui pertemuan dan pergaulan bahasa serta percakapan, tema yang diangkat ini menjelajah berbagai jarak dan kedekatan di antara berbagai ragam latar perjalanan manusia melalui penulisan puisi di Indonesia dan Australia. Karena dua negara ini begitu dekat di peta, namun seringkali, hanya di atas peta, puisi-puisi ini mengundang adanya pengaturan kembali konsep-konsep geografis kita.
Indonesia Tidak salon oleh Luna Vidya
[EasyGallery id=’lunavidya’]
*Klik pada gambar di atas untuk melihat galeri ini.
Kumpulan ini berawal dari percakapan antara Kent MacCarter dan Sapardi Djoko Damono (yang bisa dikatakan sebagai penyair kontemporer Indonesia terkemuka sekaligus ahli susastra Indonesia). Dimaksudkan untuk menciptakan media pertukaran karya terjemahan yang akan menampilkan penyair-penyair kuat yang karyanya mengemuka, dengan perwakilan seimbang dari segi gender, etnis, dan daerah di masing-masing negara. Perbincangan selanjutnya antara Kent dan John McGlynn (penerjemah sastra Indonesia ke bahasa Inggris yang termuka dan pemimpin Yayasan Lontar) adalah lantaran bagi undangan John kepada penyair Dorothea Rosa Herliany dan saya untuk ikut dalam proyek ini – undangan yang kami terima secara sangat antusias.
Selama beberapa tahun terakhir, John, Dorothea, dan saya telah bersama-sama mengerjakan The Lontar Anthology of Indonesian Poetry, sebuah antologi yang akan memuat sekian ratus karya puisi dari abad keduapuluh. Dalam proses penghimpuan karya yang akan dimuat dalam buku tsb., kami menemukan segudang karya yang ditulis oleh sekitar 1.800 penyair dengan tema-tema yang sangat beragam sebagaimana para penulis sendiri, tema-tema yang berkisah tentang sejarah dan perkembangan negeri ini yang pesat. Maka, memilih hanya sebelas penyair untuk dimasukkan dalam kumpulan ini merupakan tugas yang tidak mudah. Dalam hal pemilihan tsb., kami memprioritaskan penyair yang masih cukup muda namun telah terbukti memiliki karir kepenulisan yang mantap. Edisi istimewa Cordite Poetry Review ini merupakan perwujudan awal tujuan Antologi di atas, yakni sebuah usaha mengatasi rintangan bahasa penulisan puisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta meningkatkan keragaman lungkang meme literer pada masing-masing komunitas penulis. Kepada Kent MacCarter yang mengusulkan pengantar ini dimuat dalam dua bahasa, kami menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas undangan kerja sama kepada kami.
Salah satu ciri yang paling menonjol dari kumpulan ini—setidaknya yang langsung terlihat bagi saya ketika akhirnya saya membaca semua kumpulan puisi ini bersamaan—adalah adanya darah yang melimpah dalam teks-teks tersebut. Hal ini mengingatkan saya pada salah satu bagian dalam drama absurd karya Tom Stoppard, Rosenkratnz and Guildenstern are Dead, yang menampilkan dua tokoh minor dari karya Shakespeare, Hamlet. Tokoh-tokoh utama bertemu dengan kelompok pemain sandiwara yang menawarkan pertunjukan.
PEMAIN: ... kami bisa memainkan darah dan cinta tanpa retorika, atau darah dan retorika tanpa cinta, dan kami bisa memainkan ketiganya secara bersamaan atau bergantian, tetapi kami tidak bisa memberimu cinta dan retorika tanpa darah. Darah adalah wajib. Semuanya darah, begitu. GUILDENSTERN: Apakah ini yang orang-orang inginkan? PEMAIN: Itulah yang kami lakukan.1
Dalam beragam perenungan tentang cinta dan berbagai variasi retorika yang tampak dalam puisi di edisi jurnal ini, darah sepertinya menjadi unsure wajib. Kekerasan muncul di mana-mana, baik dalam saat-saat hening maupun dalam konteks-konteks yang banal. Di samping penggambaran baik pembantaian masal maupun pembinasaan individu, para penyair juga menyampaikan pandangan tentang kekerasan yang terjadi di tempat kerja dunia modern, brutalnya pemikiran kita yang dibentuk sewaktu masih kanak-kanak, dan serangan terhadap perasaan diri dan komunitas yang terjadi sebagai akibat dari rutinitas pekerjaan kita yang serba non-kreatif serta dorongan konsumptif yang tak ada hentinya dari media massa. Semua ini yang menjadikan kita ‘mendambakan perubahan sekonyong-konyong di dalam pembuluh darah vena’ yang akan memungkinkan kita saling menyelip satu sama lain, ‘melahap membran’ yang memisah kita, atau untuk membelahnya dengan sebuah pisau dalam pencarian kepuasan atau penderitaan.
Terkadang, puisi-puisi yang dimuat di edisi ini menekankan adanya hubungan genetika universal antara seluruh makhluk manusia dan pengalaman yang sama dialami dalam hal bertumbuh dan menua. Pada kesempatan lain, puisi-puisi ini menjadi tanda penting perbedaan-perbedaan tak terelakkan dari hak-hak kelahiran dan identitas-identitas yang dilimpahkan oleh budaya-budaya kita, yang membentangkan batas-batas antara kategori-kategori masyarakat: laki-laki/perempuan, orang ningrat /masyarakat biasa, kesukuan/kebangsaan. Seringkali mereka mengalamatkan tantangan untuk melintasi batas, untuk mencampur darah dengan darah, untuk menukar gen dan memes meskipun adanya garis-garis yang kita warisi dan bantu untuk menjaganya.
Di dalam puisi-puisi yang terkumpul di sini ada pula beberapa sajak yang menampilkan ‘cinta dan retorika tanpa darah’: misalkan sebuah puisi tentang seorang ibu, putrinya dan seekor kuda; satu tentang pengantin baru; dan satu lagi tentang tubuh kekasih di cahaya matahari. Namun puisi-puisi ini juga ternyata menuliskan tentang darah, menekan pada hasrat seksual kita dan warisan ilmu sejarah keluraga kita dengan kuda dan lumut-lumut. Sebagai sebuah kumpulan, imajinasi yang murni muncul hanya secara sepintas lalu, dan semua cinta dan retorika menjadi milik seubah narasi dimana bahkan fantasi mitologi pun menawarkan hal yang tidak lepas dari kebosanan terhadap kehidupan modern, keasingan kita satu sama lain, kecenderungan untuk melakukan perusakan kepada yang lain baik secara fisik maupun psikologis.
‘Darah’ adalah yang kita lakukan. Kita adalah makhluk yang melakukan kekerasan dan menumpahkan darah, bahkan pada yang paling dekat. Puisi-puisi ini mengingatkan kita bahwa darah adalah benang merah yang menghubungkan kita semua. Dan ini dilakukannya sembari berdebat bahwa retorika dan cinta dapat meredakan dorongan terhadap darah tersebut. ‘Hati bisa berubah’, dan puisi ini membawakan kesaksian pada kesadaran manusia yang berkecut hati melawan perusakan tubuh, menentang kekerasan yang merenggut kawan-kawan terbaik kita, kekasih-kekasih tercinta dan saudara kita yang bungsu (Puisi Joko Pinurbo berjudul ‘Mei’ mengisahkan kekerasan yang terjadi di Jakarta pada bulan Mei tahun 1998. Kata ‘Mei’ berarti bulan ‘Mei’ dalam bahasa Indonesia namun juga mempunyai arti ‘adik perempuan’ dalam bahasa China). Kumpulan ini menegaskan bahwa tubuh manusia tetaplah mejadi inspirasi wajib kita dan bahwa kekerasan apa pun yang kita lakukan, keaijiban tubuh lian akan menimbulkan dorongan untuk melintasi batas garis darah melalui puisi.
- Stoppard, Tom. 1991. Rosencrantz and Guildenstern are Dead (The Film). London: Faber and Faber, p.12. ↩